Literasi Hukum - Dalam arsitektur hukum pidana, asas legalitas (nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali) berdiri sebagai pilar utama yang menjamin kepastian hukum. Asas ini membawa konsekuensi logis berupa larangan pemberlakuan surut (non-retroaktif) terhadap suatu peraturan pidana. Tujuannya jelas: melindungi warga negara dari potensi kesewenang-wenangan negara yang menghukum perbuatan berdasarkan aturan yang dibuat post-factum (setelah fakta terjadi).
Namun, hukum bukanlah entitas yang statis. Ia bergerak dinamis merespons pergeseran nilai sosial, politik, dan keadilan masyarakat. Ketika terjadi perubahan perundang-undangan pidana, muncul ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan. Di sinilah asas Lex Favor Reo hadir sebagai pengecualian vital dari asas non-retroaktif, berfungsi sebagai jembatan keadilan dalam hukum transitoir (hukum peralihan).
Filosofi Dasar: Antara Pedang dan Timbangan
Secara terminologi, Lex Favor Reo bermakna pemberlakuan hukum yang lebih lunak atau menguntungkan bagi terdakwa. Prinsip ini menegaskan bahwa jika terjadi perubahan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan namun sebelum putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka hakim wajib menerapkan ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa.
Filosofi di balik asas ini adalah kemanusiaan. Jika kesadaran hukum masyarakat (yang direpresentasikan oleh pembentuk undang-undang) telah berubah dan memandang suatu perbuatan tidak lagi sejahat sebelumnya—atau sanksinya dianggap terlalu kejam—maka tidaklah etis bagi negara untuk tetap memaksakan hukuman berat berdasarkan aturan usang yang sudah ditinggalkan.
Landasan Normatif: Transformasi dari WvS ke KUHP Nasional
Eksistensi asas Lex Favor Reo di Indonesia memiliki akar yang kuat dan mengalami penguatan signifikan dalam rezim hukum pidana baru.
1. Rezim KUHP Lama (Wetboek van Strafrecht)
Dalam KUHP warisan kolonial, asas ini diatur dalam Pasal 1 ayat (2):
"Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan."
Pasal ini telah menjadi pedoman selama puluhan tahun, namun sering memantik perdebatan mengenai batasan "perubahan perundang-undangan" dan parameter "menguntungkan".
2. Rezim KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) memberikan pengaturan yang lebih komprehensif dan rinci dalam Pasal 3.
Tidak hanya menegaskan prinsip yang sama, KUHP Baru secara eksplisit mengatur konsekuensi teknis jika terjadi dekriminalisasi. Pasal 3 ayat (2) hingga (4) menegaskan bahwa jika perbuatan tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana menurut hukum baru, maka proses hukum harus dihentikan, dan jika sudah diputus, terpidana harus dilepaskan. Ini memberikan kepastian hukum yang jauh lebih rigid dibandingkan rezim sebelumnya.
Perdebatan Klasik: Teori Formil vs Materiil
Salah satu diskursus akademik paling alot terkait asas ini adalah menafsirkan frasa "perubahan perundang-undangan". Para ahli hukum pidana terbelah dalam beberapa pandangan:
- Teori Formil (Sempit): Tokoh seperti van Geuns berpendapat bahwa perubahan harus dimaknai secara harfiah sebagai perubahan redaksi teks undang-undang pidana itu sendiri. Perubahan pada peraturan pelaksana atau situasi faktual tidak memicu berlakunya Pasal 1 ayat (2) KUHP.
- Teori Materiil (Luas): Dianut oleh Pompe dan Jonkers, pandangan ini menyatakan bahwa perubahan perundang-undangan mencakup perubahan perasaan hukum atau keyakinan hukum masyarakat. Jika norma di luar UU Pidana berubah dan mempengaruhi sifat melawan hukum suatu perbuatan, maka asas ini harus diterapkan.
- Teori Materiil Terbatas: Jalan tengah yang sering dirujuk dalam praktik modern (sejalan dengan pandangan H.R. Utrecht) adalah perubahan di luar UU Pidana dapat dianggap sebagai perubahan perundang-undangan jika perubahan tersebut didasarkan pada perubahan penilaian hukum (gewijzigd rechtsinzicht), bukan sekadar perubahan situasi faktual.
Parameter Menentukan "Yang Paling Menguntungkan"
Dalam praktik peradilan, hakim dituntut jeli melakukan perbandingan apple-to-apple antara aturan lama dan baru secara in concreto. Parameter yang digunakan meliputi:
- Dekriminalisasi: Ini adalah bentuk paling menguntungkan. Jika aturan baru menghapus delik tersebut, maka tuntutan gugur demi hukum.
- Ancaman Pidana Pokok: Hakim membandingkan berat ringannya sanksi. Perubahan dari pidana penjara menjadi pidana denda, atau pengurangan ancaman maksimum penjara, jelas menguntungkan terdakwa.
- Perubahan Jenis Delik: Perubahan dari delik biasa menjadi delik aduan (klacht delict) sangat menguntungkan terdakwa, karena penuntutan menjadi bergantung pada ada/tidaknya aduan dari korban.
- Sistem Pemidanaan: KUHP Baru memperkenalkan pidana kerja sosial dan pengawasan sebagai alternatif penjara jangka pendek. Opsi ini tentu lebih menguntungkan dibandingkan kurungan fisik semata.
Dimensi Konstitusional: Peran Mahkamah Konstitusi
Sebagai penjaga konstitusi (The Guardian of Constitution), Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran sentral. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 memang menjamin hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights).
Namun, MK melalui berbagai putusannya menegaskan bahwa larangan retroaktif tidak berlaku jika aturan baru tersebut justru menguntungkan terdakwa (retroaktif in mitius). Asas Lex Favor Reo dipandang sebagai turunan dari hak atas keadilan yang dijamin konstitusi. Ketika MK membatalkan suatu norma pidana dalam Judicial Review, putusan tersebut sejatinya adalah "perubahan hukum" yang paling menguntungkan, sehingga harus segera diterapkan bagi mereka yang sedang menjalani proses peradilan.
Kesimpulan
Asas Lex Favor Reo adalah bukti bahwa hukum pidana Indonesia tidak menutup mata terhadap perubahan nilai keadilan. Di masa transisi pemberlakuan penuh KUHP Nasional pada tahun 2026 mendatang, pemahaman mendalam mengenai asas ini menjadi krusial bagi aparat penegak hukum, akademisi, dan praktisi hukum. Ia memastikan bahwa tidak ada warga negara yang menjadi korban dari kekakuan transisi hukum, menjunjung tinggi adagium bahwa hukum harus mengabdi pada keadilan, bukan sebaliknya.





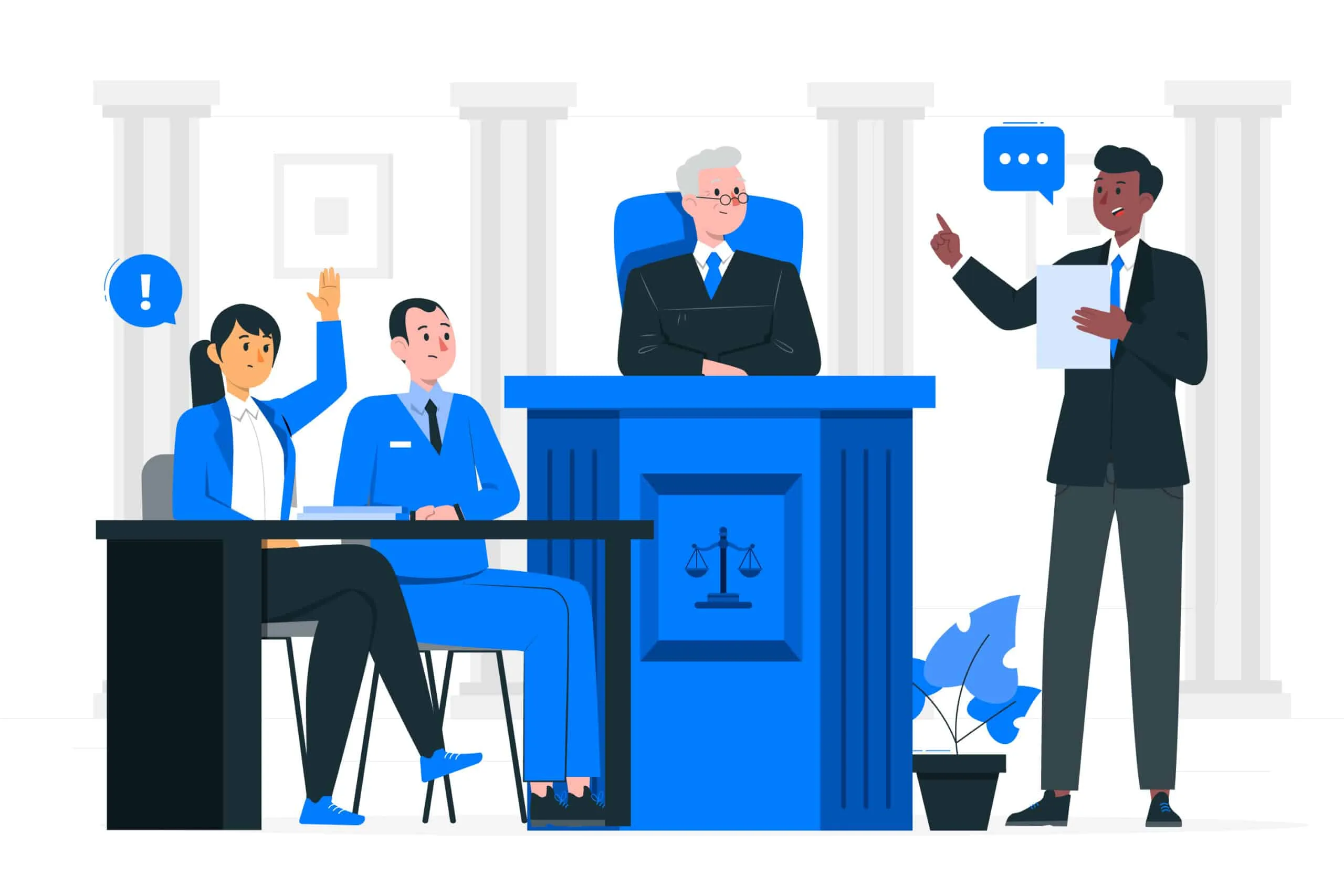






















Komentar (0)
Tulis komentar